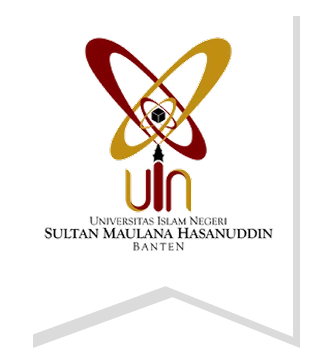Muhammad Ishom
Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Tanggal 17 Agustus selalu menjadi titik temu antara sejarah dan harapan. Melalui momentum Agustusan, bangsa Indonesia mengenang kembali perjuangan panjang menuju kemerdekaan, sembari menatap masa depan yang penuh tantangan. Namun, peringatan kemerdekaan bukan sekadar ritual tahunan. Ia seharusnya menjadi momen reflektif untuk meninjau kembali nilai-nilai dasar yang membentuk Indonesia—termasuk keislaman dan keindonesiaan.
Relasi antara Islam dan Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah bangsa ini. Islam tidak hadir sebagai kekuatan asing, tetapi tumbuh secara organik di tengah masyarakat Nusantara, menyatu dengan budaya, dan turut membentuk struktur sosial serta etika publik. Peran umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan, baik melalui jalur politik maupun kultural, menjadi bukti nyata bahwa keislaman dan keindonesiaan bukan dua kutub yang berlawanan, melainkan dua kekuatan yang saling menguatkan.
Namun, perkembangan mutakhir menunjukkan adanya jarak yang mulai melebar antara ekspresi keislaman dan identitas kebangsaan. Sebagian kelompok mencurigai nasionalisme sebagai bentuk sekularisme yang mengikis iman, sementara sebagian lain memandang simbol-simbol keislaman sebagai ancaman terhadap pluralitas. Narasi ini, jika terus dibiarkan, berisiko merusak tenun kebangsaan yang selama ini dijaga melalui dialog, toleransi, dan semangat gotong royong.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merestorasi keislaman dan keindonesiaan secara bersamaan. Restorasi di sini bukan dalam arti mengembalikan kepada bentuk lama, melainkan memperbaharui spirit keduanya agar lebih relevan dengan konteks kekinian. Keislaman yang direstorasi adalah keislaman yang mencerminkan nilai-nilai universal Islam: keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan penghargaan terhadap kehidupan. Sementara keindonesiaan yang direstorasi adalah keindonesiaan yang menjunjung tinggi kebhinekaan, menjamin keadilan sosial, dan membuka ruang partisipasi bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.
Kita tidak kekurangan sumber daya untuk melakukan ini. Tradisi keislaman di Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, mulai dari pemikiran ulama klasik, khazanah pesantren, hingga praktik sosial Islam Nusantara yang adaptif dan damai. Demikian pula dengan keindonesiaan yang dibangun di atas fondasi Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang dibutuhkan adalah komitmen kolektif untuk menjembatani kembali kedua kutub ini ke dalam ruang publik, pendidikan, dan kebijakan.
Pendidikan memiliki peran sentral dalam proses restorasi ini. Generasi muda harus diajarkan bahwa menjadi Muslim yang taat dan menjadi warga negara yang baik bukanlah dua identitas yang bertabrakan. Kurikulum sekolah, narasi media, serta peran keluarga harus diarahkan untuk membentuk pribadi yang religius sekaligus nasionalis. Ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan berdaya saing.
Momentum kemerdekaan tahun ini pun seharusnya dijadikan ajang refleksi bersama. Kita patut bertanya: apakah kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun benar-benar telah membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan? Apakah nilai-nilai Islam yang mendorong perlawanan terhadap kolonialisme dulu masih hidup dalam praktik sosial kita hari ini?
Realitasnya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Ketimpangan ekonomi yang tinggi, maraknya korupsi, intoleransi yang muncul di ruang digital, serta krisis kepercayaan terhadap institusi publik menjadi indikator bahwa nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan perlu terus dirawat. Dalam konteks ini, restorasi bukanlah slogan, melainkan kerja nyata yang dimulai dari diri sendiri dan diperluas ke lingkungan sosial yang lebih luas.
Restorasi juga menuntut keteladanan. Para tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan pejabat publik harus menjadi contoh dalam mempertemukan agama dan kebangsaan secara harmonis. Bukan hanya melalui pidato, tetapi melalui sikap, keputusan, dan komitmen pada etika. Kepemimpinan moral menjadi kebutuhan mendesak agar rakyat tidak terjebak pada ekstremisme atau apatisme.
Ke depan, tantangan global—baik berupa disrupsi teknologi, perubahan iklim, maupun krisis geopolitik—akan semakin memerlukan bangsa yang kokoh identitasnya, namun terbuka pada kemajuan. Islam yang moderat dan keindonesiaan yang toleran adalah dua fondasi penting untuk menjawab tantangan tersebut. Kita harus berani melangkah melampaui dikotomi lama antara agama dan negara, dan membangun sintesis baru yang kontekstual, kreatif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.
Merayakan kemerdekaan bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi merumuskan arah masa depan. Dan masa depan itu hanya bisa dicapai jika kita mampu merestorasi nilai-nilai luhur yang menjadi roh dari republik ini. Islam dan Indonesia bukan dua jalan yang berbeda, tetapi dua sisi dari satu cita-cita besar: membangun peradaban yang adil, beradab, dan manusiawi.