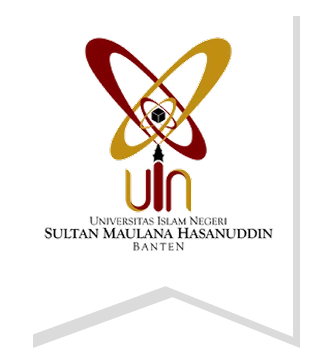HumasUIN – Di era digital yang serba terkoneksi, profesi influencer telah menjelma menjadi salah satu pekerjaan paling diminati, terutama oleh generasi muda. Berbekal kemampuan menciptakan konten dan membangun audiens, seorang influencer dapat memperoleh penghasilan yang luar biasa besar. Di Tiongkok, misalnya, seorang influencer ternama seperti Crazy Xiaoyangge dilaporkan mampu menghasilkan hingga 451 juta dolar AS per tahun, setara dengan sekitar tujuh triliun rupiah. Angka ini melampaui penghasilan banyak profesional di bidang konvensional seperti dokter, pengacara, atau insinyur. Namun di sisi lain, sebagian besar influencer lain justru berpenghasilan jauh lebih kecil, menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar di dunia profesi baru ini.
Jika dibandingkan dengan profesi tradisional, penghasilan influencer tampak sangat kontras. Seorang insinyur atau manajer menengah di Tiongkok rata-rata menerima gaji sekitar 29 ribu yuan per bulan (sekitar 4 ribu dolar AS). Sementara itu, mayoritas influencer pemula di negara yang sama hanya memperoleh sekitar 5 ribu yuan (sekitar 700 dolar AS) per bulan. Artinya, menjadi influencer adalah pekerjaan berisiko tinggi dengan potensi imbalan luar biasa, namun tanpa jaminan kestabilan. Perbandingan ini menggambarkan bahwa profesi influencer menyerupai permainan peluang: ada yang berhasil mencapai puncak popularitas dan kekayaan, tetapi lebih banyak yang tertinggal di bawah tanpa perlindungan ekonomi yang memadai.
Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan penting: apakah profesi influencer seharusnya diatur dan diakui secara formal sebagaimana profesi lain? Gagasan sertifikasi influencer muncul sebagai jawaban untuk menciptakan standar kompetensi dan etika dalam industri ini. Sertifikasi dimaksudkan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk memberikan kerangka profesional yang lebih jelas, sehingga para influencer dapat bekerja dengan tanggung jawab dan kredibilitas yang lebih tinggi. Dengan adanya sertifikasi, influencer diharapkan tidak hanya menjadi figur populer, tetapi juga komunikator yang memahami dampak sosial dan ekonomi dari setiap konten yang mereka buat.
Sertifikasi influencer dapat mencakup berbagai aspek penting seperti pelatihan literasi media, etika komunikasi digital, dan pengetahuan dasar tentang peraturan iklan serta perlindungan konsumen. Selain itu, sertifikasi bisa berfungsi sebagai alat verifikasi keahlian bagi influencer yang berbicara di bidang-bidang profesional seperti kesehatan, hukum, keuangan, atau pendidikan. Dengan demikian, masyarakat memiliki jaminan bahwa konten yang mereka konsumsi berasal dari sumber yang kompeten dan dapat dipercaya.
Dalam konteks global, Tiongkok menjadi salah satu negara pertama yang menerapkan kebijakan serupa. Pemerintah di sana mewajibkan influencer dan streamer yang membahas isu-isu profesional untuk memiliki kualifikasi akademik atau sertifikat di bidang yang relevan. Misalnya, seseorang yang membuat konten edukasi hukum harus memiliki latar belakang pendidikan hukum, dan kualifikasi tersebut diverifikasi oleh platform tempat ia beroperasi. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Tiongkok dalam menertibkan ruang digital dan memastikan bahwa pengaruh sosial para kreator tidak disalahgunakan.
Kebijakan ini tidak muncul tanpa alasan. Di Tiongkok, industri influencer berkembang pesat dan memiliki dampak ekonomi yang besar, terutama dalam sektor e-commerce. Namun, maraknya konten menyesatkan dan promosi produk tanpa dasar ilmiah menimbulkan kekhawatiran publik. Pemerintah menilai bahwa pengaruh seorang influencer bisa menyamai atau bahkan melampaui media tradisional, sehingga diperlukan tanggung jawab profesional yang sepadan. Dengan sertifikasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap opini yang disiarkan memiliki dasar keilmuan dan tidak merugikan masyarakat.
Namun, kebijakan semacam ini juga menimbulkan dilema. Di satu sisi, sertifikasi dapat meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik. Di sisi lain, ia berisiko menekan kebebasan berekspresi dan menghambat kreator muda yang belum memiliki akses terhadap pendidikan formal. Tantangannya terletak pada bagaimana menciptakan sistem sertifikasi yang inklusif dan adaptif terhadap keberagaman konten kreator, tanpa mengubah dunia digital menjadi ruang yang terlalu birokratis.
Di Indonesia, gagasan serupa mulai mengemuka seiring meningkatnya jumlah influencer dan besarnya pengaruh mereka terhadap perilaku konsumen. Sertifikasi bisa menjadi langkah awal untuk menata ekosistem kreator digital agar lebih profesional. Misalnya, lembaga seperti Kominfo atau asosiasi industri digital dapat bekerja sama untuk membuat standar etika dan kompetensi dasar bagi influencer. Sistem ini juga bisa memberikan keuntungan bagi brand dan platform, karena mereka dapat lebih mudah bekerja dengan influencer yang memiliki kredibilitas dan reputasi terverifikasi.
Akhirnya, sertifikasi influencer bukan hanya soal pengakuan formal, tetapi tentang tanggung jawab sosial dalam dunia yang semakin dipengaruhi oleh media digital. Seorang influencer kini bukan sekadar pembuat konten, melainkan pembentuk opini publik dan perilaku massa. Dengan sertifikasi yang tepat, profesi ini dapat berkembang sebagai karier yang beretika, berkompeten, dan berkelanjutan yang setara dengan profesi-profesi lain yang lebih dulu diakui negara. Dunia digital membutuhkan figur yang bukan hanya viral, tetapi juga dapat dipercaya; dan sertifikasi mungkin menjadi kunci menuju ekosistem influencer yang lebih sehat dan profesional.